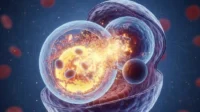Oleh: Kang Oos Supyadin
“Publik dikejutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang membuka jalan bagi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk diangkat sebagai ASN PPPK. Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan mengusulkan pengangkatan 32.000 pekerja SPPG menjadi ASN PPPK. Bagi para guru honorer dan guru swasta yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun justru tanpa kepastian status. Kebijakan ini terasa sebagai ironi.”
SEJAK Republik ini berdiri, pendidikan selalu disebut sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Konstitusi menegaskan kewajiban negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Namun dalam praktiknya, tata kelola pendidikan nasional masih menyimpan persoalan laten yang tak kunjung tuntas: nasib guru honorer dan guru swasta.
Mereka mengajar di ruang-ruang kelas yang sama, memikul tanggung jawab yang sama, bahkan menghadapi tantangan yang sama dengan guru ASN dan PPPK. Bedanya hanya satu: status dan kesejahteraan. Selama puluhan tahun, alasan klasik keterbatasan anggaran negara menjadi dalih untuk menunda penyelesaian persoalan ini. Dari satu rezim ke rezim berikutnya, janji penataan status dan peningkatan kesejahteraan guru honorer kerap digaungkan, namun realisasinya berjalan tersendat.
Data terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan informasi terkait kebijakan ASN hingga akhir tahun 2025, Jumlah Guru Honorer diperkirakan sekitar 2,6 juta yang belum berstatus ASN atau PPPK. Namun, data lain menyebutkan sisa tenaga honorer di tahun 2026 menjadi sekitar 237 ribu.
Persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut arah kebijakan dan prioritas negara. Guru adalah pondasi esensi dalam sukses atau tidaknya pendidikan nasional kita. Kalau pondasinya rapuh, bangunan besar bernama Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan.
Di tengah persoalan lama yang belum selesai, publik dikejutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang membuka jalan bagi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk diangkat sebagai ASN PPPK. Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan mengusulkan pengangkatan 32.000 pekerja SPPG menjadi ASN PPPK.
Kebijakan ini sontak memicu polemik. Bagi sebagian kalangan, langkah tersebut dipandang sebagai bentuk keseriusan negara terhadap program pemenuhan gizi. Namun bagi para pendidik honorer dan guru swasta yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun tanpa kepastian status, kebijakan ini terasa sebagai ironi.
Negara seperti melompat pada program baru, sementara pekerjaan rumah lama di bidang pendidikan belum tuntas. Ini bukan soal menolak program MBG, tetapi soal keberpihakan dan skala prioritas.
Guru Honorer: Abdi Negara Tanpa Kepastian
Data dan fakta di lapangan menunjukkan ribuan guru honorer masih menerima honor di bawah standar kelayakan. Guru honorer masih ada yang digaji Rp 500 ribu per bulan, jauh dari standar upah minimum. Mereka tetap mengajar dengan dedikasi tinggi, mengisi kekosongan formasi ASN, bahkan menjadi tulang punggung sekolah-sekolah.
Namun, pengabdian para guru honorer di pelosok desa atau di sudut kota yang padat, setiap pagi tetap berdiri di depan papan tulis, mengajar, membina anak bangsa dengan penuh tanggung jawab. Kapurnya mulai menipis. Sepatunya sudah aus. Honor yang diterima tiap bulan bahkan kadang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ia tidak pernah bertanya atau menyampaikan “kata hati”; apakah murid-muridnya tahu statusnya, honorer atau ASN. Ia hanya ingin muridnya bisa membaca, bisa berhitung, dan bisa menggapai cita-cita menjadi generasi yang berguna untuk negeri ini.
Guru selalu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun bagi ribuan guru honorer dan guru swasta, frasa itu terasa semakin harfiah: tanpa tanda, tanpa kepastian, tanpa jaminan kesejahteraan.
Mereka mengerjakan tugas yang sama dengan guru ASN dan PPPK. Mereka menyusun RPP, memeriksa tugas, menghadiri rapat, mendampingi siswa lomba, bahkan menjadi orang tua kedua di sekolah. Tetapi ketika bicara soal status dan perlindungan, mereka sering berada di barisan paling belakang.
Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mereka menunggu. Menunggu janji penataan. Menunggu afirmasi. Menunggu kepastian yang tak kunjung benar-benar datang. Selama ini, mereka dijanjikan skema pengangkatan bertahap, afirmasi khusus, hingga penyederhanaan seleksi PPPK. Namun prosesnya kerap berbelit, kuota terbatas, dan tidak semua memenuhi persyaratan administratif yang kian kompleks.
Di sisi lain, program MBG baru berjalan sekitar satu tahun. Program ini tentu memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun dalam perspektif kebijakan publik, muncul pertanyaan: apakah wajar sebuah unit pelaksana program yang relatif baru justru memperoleh percepatan jalur pengangkatan ASN, sementara guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun masih menunggu?
Dalam kerangka pembangunan nasional, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak instan, tetapi dampaknya sistemik dan berkelanjutan. Kualitas guru menentukan kualitas peserta didik, dan pada akhirnya menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Bahwa program sosial seperti MBG memang penting, tetapi tidak boleh menggeser fokus pada penataan sistem pendidikan. “Kalau negara serius ingin membangun generasi unggul, maka penyelesaian status dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama. Itu fondasinya.”
Setiap program ada sebuah potensi risiko. Program pemerintah bisa saja berubah seiring dinamika politik dan fiskal. Jika suatu saat program tersebut dihentikan atau direstrukturisasi, bagaimana nasib ASN PPPK yang diangkat melalui jalur tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan.
Polemik ini sejatinya bisa menjadi momentum refleksi bagi pemerintah di era Presiden Prabowo. Penyelesaian masalah guru honorer dan guru swasta tidak hanya soal keadilan, tetapi juga soal konsistensi arah pembangunan dibidang pendidikan sebagai modal dasar dalam rangka mencerdaskan anak bangsa.
Dengan adanya kepastian kebijakan yang komprehensif dan berpihak pada tenaga pendidik, setidaknya satu simpul besar dalam persoalan pendidikan nasional dapat terurai. Negara perlu menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas, terukur, dan berkelanjutan untuk penataan status guru, bukan sekadar solusi tambal sulam.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya sederhana: kepada siapa negara lebih dulu memberi kepastian? Kepada mereka yang baru direkrut untuk menjalankan program baru, atau kepada para pendidik yang telah lama mengabdi tanpa kepastian? Di sinilah ukuran keberpihakan diuji.–(***)
Rahayu.
*). Kang Oos Supyadin SE MM, Pemerhati Kebijakan Publik, tinggal di Kota Garut, Jawa Barat