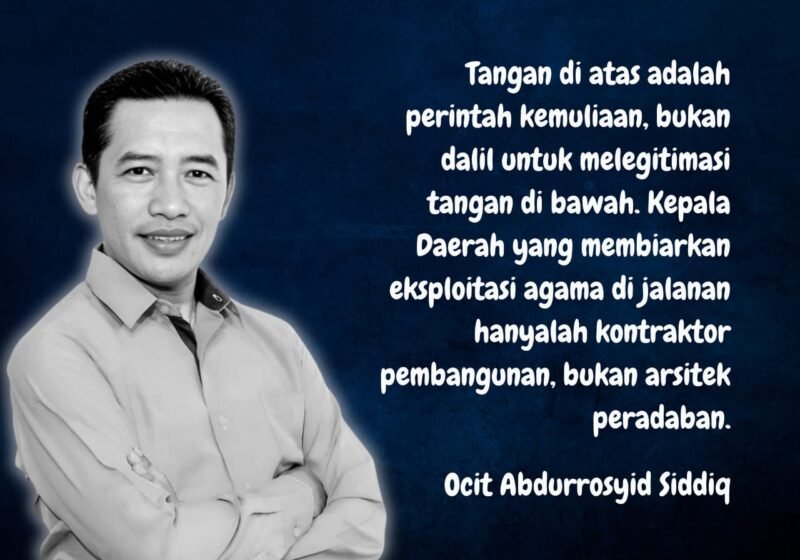Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
BERDIRI di persimpangan lampu merah kota-kota besar di Indonesia adalah cara tercepat membaca wajah asli pembangunan. Saat lampu menyala merah, sebuah drama sosial langsung terbentang: pengamen dengan gitar lusuh, manusia patung berwajah perak, anak-anak kecil menawarkan tisu, hingga orang-orang yang menyodorkan gelas plastik sambil melafalkan dalil agama. Di titik itulah, narasi besar tentang kemajuan ekonomi kerap runtuh tanpa perlawanan.
Sebuah kota dengan gedung menjulang dan trotoar berkilau tak serta-merta layak disebut maju jika di kaki-kakinya masih berkeliaran warga yang terpaksa menjual rasa iba demi bertahan hidup. Ukuran paling sederhana dari keberhasilan seorang kepala daerah sejatinya bukan seberapa indah wajah kota dipoles, melainkan sejauh mana ia mampu memastikan warganya tidak lagi menggantungkan hidup pada belas kasihan di jalanan.
Sayangnya, banyak pemimpin daerah terjebak pada ilusi keberhasilan. Mereka berbangga ketika kawasan yang dulu kumuh disulap menjadi “ikon wisata”, ketika taman kota dipercantik hingga menyerupai Malioboro, Braga, atau sudut-sudut estetik kota lain. Padahal, pembangunan fisik semacam itu hanyalah pekerjaan infrastruktur—siapa pun yang memegang anggaran bisa melakukannya.
Trotoar berlapis keramik dan lampu kota yang temaram tak lebih dari kosmetik jika di atasnya masih berkeliaran penyandang masalah sosial yang dibiarkan tanpa arah dan solusi. Pembangunan batu dan besi menjadi hampa ketika manusia di sekitarnya luput dari sentuhan kebijakan.
Ujian sesungguhnya seorang kepala daerah bukanlah membangun taman, melainkan membangun manusia. Keberhasilan kepemimpinan tidak diukur dari mengkilapnya ubin trotoar, tetapi dari “menghilangnya” masalah sosial dari ruang publik—bukan karena disapu paksa, melainkan karena mereka telah diberdayakan, direhabilitasi, dan diberi kesibukan yang bermartabat.
Selama aktor-aktor jalanan itu masih menjamur, itu adalah penanda kegagalan kepemimpinan. Seorang kepala daerah mungkin piawai sebagai arsitek kota, tetapi gagal total sebagai nakhoda sosial yang seharusnya menjamin martabat warganya.
Kesan semu kemajuan kian pahit ketika kita menyaksikan eksploitasi kemiskinan yang dibungkus narasi ketuhanan. Tak sedikit pengemis yang melontarkan ayat-ayat suci sebagai alat legitimasi. Ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan distorsi teologis yang serius. Perintah agama untuk bersedekah adalah instrumen etika bagi yang mampu, bukan “karcis moral” untuk membenarkan kemalasan atau praktik meminta-minta.
Menjual ayat suci di persimpangan jalan adalah penghinaan terhadap esensi agama itu sendiri—agama yang justru menjunjung tinggi kerja keras, harga diri, dan kemuliaan tangan di atas.
Keadaban kota makin tergerus ketika anak-anak kecil berlarian di antara deru kendaraan, mempertaruhkan nyawa demi receh. Pedagang asongan dan PKL berebut ruang dengan aspal di titik-titik terlarang. Ini bukan semata potret kegigihan ekonomi rakyat kecil, melainkan bukti kegagalan negara menyediakan ruang niaga yang layak serta kegagalan melindungi hak-hak anak.
Membiarkan anak-anak bekerja di jalanan saat jam sekolah adalah dosa kepemimpinan yang nyata. Itu menandakan bahwa sistem wajib belajar dan perlindungan anak hanya berhenti sebagai slogan kebijakan.
Belum lagi fenomena “Pak Ogah” dan juru parkir liar yang memanipulasi ruang publik, menciptakan kemacetan buatan, memalak di depan minimarket dan ATM. Premanisme terselubung ini tumbuh subur karena lemahnya wibawa hukum dan absennya sistem pengelolaan ruang publik yang tegas.
Jika praktik-praktik ini terus dibiarkan—bersamaan dengan eksploitasi anak dan kesemrawutan kota yang dibungkus estetika—maka kemajuan itu sejatinya adalah kepalsuan.
Kegagalan ini bersifat sistemik. Ia menandakan Dinas Sosial yang terjebak razia seremonial tanpa rehabilitasi transformatif. Dinas Perhubungan yang gagal membangun sistem parkir modern bebas pungli. Dan Dinas Tenaga Kerja yang tak mampu menciptakan jaring pengaman bagi warga berdaya saing rendah.
Pemimpin yang gagal adalah mereka yang membiarkan masalah ini tetap ada dengan dalih “terlalu kompleks untuk diselesaikan”.
Masyarakat hari ini berhak menuntut lebih dari sekadar kota yang cantik. Kota yang maju bukanlah tempat di mana orang miskin dipaksa tampil rapi di tengah kemiskinannya, melainkan tempat di mana mereka memiliki martabat untuk tidak mengemis. Kita merindukan kota yang sepi dari peluit parkir liar, bersih dari pedagang yang bertaruh nyawa di lampu merah, dan sunyi dari tangis anak-anak penjual tisu.
Bukan karena mereka diusir, melainkan karena mereka telah diberi ruang, pendidikan, dan pekerjaan yang manusiawi oleh sistem yang dibangun pemimpinnya.
Sebagai penutup, ketika seorang kepala daerah membanggakan trotoar baru sementara di bawahnya masih ada pengemis yang “menjajakan” ayat suci demi menutupi keputusasaan, maka sesungguhnya ia sedang memamerkan kegagalannya sendiri. Ketertiban ruang publik dan terjaganya martabat warga adalah etalase paling jujur dari kompetensi seorang pemimpin.
Tanpa itu, pembangunan hanyalah panggung sandiwara: indah di mata wisatawan, namun perih di hati warga yang mendambakan keadilan dan martabat yang hakiki.–(***)
*).Penulis, Pengurus ICMI Orwil Banten, Pengamat Media dan Kebijakan Publik