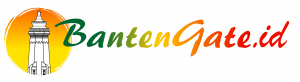Oleh: H. Edi Murpik
(Murid TQN Ponpes Cicapar, Garut – Jawa Barat)
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, memantik perdebatan panjang di ruang publik. Sebagian masyarakat menyambutnya sebagai pengakuan atas kontribusi Soeharto dalam pembangunan Indonesia modern. Namun sebagian lainnya menolak dengan alasan catatan kelam Orde Baru: pelanggaran HAM, pembungkaman politik, hingga gaya kepemimpinan yang dinilai otoriter.
Sepekan sebelum gelar tersebut ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November 2025, saya secara tidak sengaja bertemu seseorang di sebuah warung kopi di Rangkasbitung, Banten. Rambutnya gondrong sebahu, pembawaannya tenang. Dari sikap dan caranya berbicara, saya yakin ia bukan orang sembarangan. Obrolan ringan kami mengalir ke berbagai hal—tentang Lebak, tentang Banten, dan keadaan negara, sambil menikmati secangkir kopi.
Ia kemudian bertanya tentang pandangan saya mengenai rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Pak Soeharto. Saya menjawab; “Setiap orang berhak berpendapat. Setiap manusia punya sisi baik dan kekurangan. Tetapi saya pernah hidup pada masa pemerintahan Pak Harto. Dan saya sangat setuju.”
Jejak Soeharto di Kabupaten Lebak
Pak Soeharto pernah dua kali berkunjung ke Kabupaten Lebak. Kunjungan pertama terjadi sekitar tahun 1971, ketika ia datang menemui rekan seperjuangannya, Abah Jaro Karis, tokoh karismatik di Cisimeut, Leuwidamar. Saat itu saya masih sekolah SD kelas V dan orang tua saya hendak mengajak saya untuk ikut, menyaksikan kedatangan Pak Harto. Tapi, saat itu saya sedang sakit demam. Saat kunjungan itu, Bupati Lebak di jabat RD Hardiwinangoen.
Kunjungan kedua berlangsung sekitar tahun 1981, ketika Soeharto meresmikan perkebunan NES V (Nucleus Estate and Smallholders V) atau PIRBUN V— pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR) dan kebun plasma—di Kertajaya, Kecamatan Banjarsari, sekitar 97 kilometer dari Rangkasbitung.
Saya masih ingat jelas sosoknya: mengenakan safari abu-abu dan peci hitam, menyapa warga dengan senyum khasnya. Sebagian sahabat yang menjadi anggota Pramuka di SMAN 1 Rangkasbitung turut menyambut kedatangannya di bawah bimbingan Pak Nazaruin Datuk Pamuncak, guru Ekonomi sekaligus Pembina Pramuka.
Beberapa foto kunjungan tersebut—jepretan almarhum Mang Ata Samsudin, fotografer Kantor Departemen Penerangan RI—sempat saya simpan dalam sebuah album. Foto-foto itu kini menjadi kenangan yang melekat kuat dalam ingatan.
Soeharto Bapak Pembangunan
Bagi sebagian kalangan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dianggap tidak layak. Tragedi 1965, pembungkaman pers, kontrol politik yang ketat, serta dugaan praktik korupsi pada masa akhir kekuasaan menjadi dasar utama penolakan itu.
Namun bagi kelompok pendukung, Soeharto dianggap sebagai figur yang mampu menata ulang negara pasca-kekacauan politik 1965. Ia dipandang sebagai penyelamat ekonomi yang membawa Indonesia menuju pertumbuhan stabil, sekaligus pemimpin yang membangun fondasi pembangunan nasional.
Sejarah memang tidak pernah hitam putih—dan Soeharto adalah salah satu tokoh yang memantulkan kompleksitas itu.
Sebelum memasuki panggung kekuasaan, ia merupakan pejuang yang ikut bertempur mempertahankan kemerdekaan. Soeharto bergerilya dari kampung ke kampung, memimpin pasukan dalam keterbatasan, dan menghadapi ketidakpastian di masa-masa awal republik.
Pengalaman tempur itu membentuk karakter khasnya: tenang, penuh perhitungan, jarang bereaksi emosional. Sifat ini melekat hingga akhir hayatnya.
Sebesar apa pun kontroversinya, sejumlah capaian pembangunan Soeharto sulit diabaikan. Di antaranya; Swasembada Beras 1984, capaian penting yang membuat Indonesia dipandang sebagai negara agraris berdaulat pangan; Pembangunan infrastruktur masif: bendungan, jalan raya, irigasi, pelabuhan, dan elektrifikasi desa; Stabilisasi ekonomi nasional pada 1970–1990 yang mendorong pertumbuhan tinggi; Program Wajib Belajar, membuka akses pendidikan hingga pelosok desa; dan Penurunan angka kemiskinan, dari lebih dari 40 persen menjadi sekitar 11 persen.
Warisan inilah yang membuat sebagian masyarakat memandangnya layak menyandang gelar Pahlawan Nasional.
Soeharto dan Kisah Sunyi Seorang Murid TQN
Di luar gemuruh dunia politik, Soeharto menyimpan sisi spiritual yang jarang diketahui publik. Ia merupakan murid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN) yang berpusat di Pesantren Suralaya, Tasikmalaya.
Sekitar tahun 1983, Soeharto menerima talqin dzikir dari Pangersa Abah Anom (KH. A. Shohibulwafa Tajul Arifin). Prosesi berlangsung sederhana, tanpa seremoni istana.
Kesaksian itu, muncul dari Haji Mujiono, Kepala Protokol Istana, sebagaimana beredar melalui tulisan Ang Abi Raden di laman media sosial. Satu bulan setelah Soeharto menerima talqin, Mujiono, sowan ke Suralaya bersama keluarganya. Ia bertanya kepada Pangersa Abah:
“Abah, diapakan Bapak Presiden? Kami sekeluarga juga ingin itu.”
Pangersa Abah tersenyum dan mempersilakan mereka berwudu sebelum memberikan talqin dzikir.
Mujiono kemudian bercerita:
“Sejak mendapatkan talqin, Pak Harto meminta kami selalu salat berjamaah. Beliau juga meminta agar tidak ada agenda istana pada waktu waktu sholat Magrib dan sholat Isya.”
Dalam perjalanan dinas ke luar negeri, Soeharto tidak pernah keluar kamar pada waktu-waktu tertentu, karena tengah mengamalkan dzikir yang diajarkan gurunya. Kebiasaan ini dijalaninya selama lebih dari dua dekade, hingga akhir hayat.
Di masa pensiun, Soeharto semakin tekun beribadah: memperbanyak dzikir, puasa sunah, dan salat malam. Ia memilih hidup lebih tenang—menjauh dari hiruk-pikuk politik dan sorotan media. Kesunyian menjadi ruang perenungan dan penguatan spiritual yang ia jalani tanpa pamer.
Sebagaimana ajaran dzikir khafi dalam TQN, Soeharto menjalani religiusitasnya dalam keheningan.
Kesaksian tentang talqin dzikir Soeharto juga pernah disampaikan guru saya, Ajengan Abah Haji Zaenal (alm) dan Ajengan Abah Haji Uti (alm), pemimpin Pesantren TQN Cicapar, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kedua orang guru saya adalah penerus dari Ki Samsudin, Kicau, Tasikmalaya.
Soeharto adalah figur paradoks: pahlawan bagi sebagian, trauma bagi sebagian lainnya. Ia pemimpin kuat sekaligus kontroversial; pembangun sekaligus penguasa; dihormati sekaligus dikritik.
Tetapi di balik seluruh perdebatan, ia tetap manusia—seorang hamba yang mencari ketenangan, seorang murid yang mendapat bimbingan mursyid, seorang muslim yang beribadah hingga akhir hayat.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional mungkin tak akan memuaskan semua pihak. Namun mengabaikan seluruh jejak hidup Soeharto—sebagai pejuang, pemimpin pembangunan, maupun penempuh jalan spiritual—akan membuat sejarah kehilangan kedalaman.
Soeharto bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Ia cermin bahwa setiap pemimpin, setinggi apa pun kedudukannya, tetaplah manusia dengan sisi terang dan gelap. Di Suralaya, ia menemukan ketenangan. Di Indonesia, ia meninggalkan warisan—yang dipuji maupun dikritik. Dan sejarah, seperti manusia, tidak pernah benar-benar hitam atau putih.—(***)