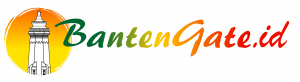Oleh: H. Edi Murpik
(Pegiat Seni dan Budaya di Banten)
KITA hidup di masa ketika anak-anak lebih hafal lirik lagu Korea atau pop barat dari pada pupuh Kinanti atau Asmarandana. Bahasa daerah pun kian jarang terdengar di rumah, sekolah, bahkan ruang publik. Banyak anak muda sekarang yang merasa canggung ketika berbicara dalam bahasa ibu mereka sendiri. Inilah tanda-tanda kemunduran kultural yang sesungguhnya—bukan karena kehilangan teknologi, tapi kehilangan jati diri.
Di tengah realitas itu, Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), digelar oleh sejumah Sekolah Dasar (SD) dan SLTP di tingkat kecamatan se-Kabupaten Lebak, pada 23 Oktober 2025 lalu. Dari 28 kecamatan yangada di Lebak, tak seluruhnya menyelenggarakan FTBI, karena minimnya fasilitas dan ketidaktersediaan anggaran.
Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) di Kabupaten Lebak, sejatinya bukan sekadar perlombaan antar pelajar. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan gerakan kebudayaan yang layak diapresiasi dan diperkuat oleh seluruh pemangku kebijakan. Pagelaran FTBI sebagai upaya untuk membangkikan kembali semangat cinta bahasa dan seni daerah di kalangan generasi muda, ketika bahasa dan seni daerah mulai ditinggalkan anak bangsa.
Salah satu kisah inspiratif dari ajang FTBI tahun ini datang dari Raska Al Ghifari, murid SDN 2 Muara Ciujung Timur, yang meraih juara dalam lomba Ngawih tingkat Kecamatan Rangkasbitung.
Raska, menyanyikan lagu-lagu daerah Sunda dengan laras, cengkok, dan penghayatan khas. Prestasi Raska bukan sekadar kemenangan individu, melainkan simbol dari semangat anak-anak Lebak untuk tetap menjaga warisan budaya leluhur di tengah perubahan zaman
Anak sulung dari pasangan Dimas dan Nurul, ternyata belajar ngawih secara otodidak lewat tutorial Channel YouTube: Kantor Bahasa Pemerintah Provinsi Banten, Kemendikdasmen. Dalam channel tersebut, Raska, belajar menirukan cara nyanyi lagu Uti-Uti Uri, Lutung Kasarung, dan kawih sunda lainya.
Olah vocal yang ia lakukan, menjiplak sekar (ngawih) yang ada dalam kanal youtube tersebut, karena tak ada guru karawitan di sekolahnya. Tapi semangatnya melampaui keterbatasan. Suara Raska yang melantunkan pupuh Asmarandana bukan hanya musik, melainkan pernyataan identitas: kami masih ada, kami masih cinta budaya Sunda.
FTBI dan Gerakan Revitalisasi Bahasa Daerah
FTBI merupakan bagian dari Gerakan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini dijalankan lewat Balai Bahasa di tiap provinsi, termasuk Balai Bahasa Provinsi Banten, untuk melestarikan dan menghidupkan kembali bahasa ibu di sekolah.
Tujuan besarnya bukan semata-mata pelestarian linguistik, tetapi juga penguatan karakter dan identitas nasional melalui budaya lokal. Bahasa daerah, termasuk bahasa Sunda, adalah wadah nilai-nilai moral, etika, dan kearifan yang diwariskan turun-temurun.
Kegiatan FTBI bukanlah akhir dari program revitalisasi, melainkan bagian penting dari upaya pelestarian berkelanjutan. FTBI merupakan wadah apresiasi penutur muda bahasa Sunda yang telah menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa dan budaya Sunda. Lomba yang digelar—mulai dari nembang pupuh, biantara, ngarang carpon, maca jeung tulis aksara Sunda, borangan (komedi tunggal), maca sajak, hingga ngadongeng—menjadi ruang ekspresi generasi muda untuk memartabatkan bahasa ibu mereka.
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo, dari 718 bahasa daerah di Indonesia, ratusan bahasa daerah dalam kondisi terancam. Bahkan bahasa-bahasa besar seperti Sunda dan Jawa yang dikategorikan “aman” pun mulai kehilangan penuturnya di generasi muda.
Imam Budi Utomo, mengingatkan ancaman serius terhadap bahasa daerah. Dari 718 bahasa daerah di Indonesia, sebelas sudah punah dan sebagian besar lainnya terancam.
“Bahasa Sunda dan Jawa yang dianggap aman pun tidak sepenuhnya aman. Coba lihat, seberapa banyak anak muda kini yang bisa membaca aksara Sunda atau menembang pupuh?” ujarnya dalam pembukaan FTBI tingkat provinsi di Bandung, 7 Oktober 2025, seperti ditulis di laman Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi 8 Oktober 2025.
Pesan itu menjadi relevan bagi daerah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten: pelestarian budaya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus menjadi gerakan kolektif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. FTBI, bukan proyek seremonial tahunan. Ia adalah gerakan penyadaran kolektif: bahwa bahasa ibu adalah napas kebudayaan. Tanpa bahasa daerah, lenyap pula rasa, nilai, dan pandangan hidup masyarakat lokal.
Musik, Nilai, dan Filsafat Hidup Orang Sunda
Salah satu bentuk seni yang diangkat dalam FTBI adalah Ngawih atau Sekar Sunda, yaitu seni tembang tradisional yang diwariskan dari masa ke masa. Dalam tradisi Sunda, ngawih bukan sekadar bernyanyi, tapi juga bermeditasi dalam keindahan bahasa dan rasa.
Setiap pupuh memiliki laras, watak, dan ajaran moral tersendiri: Kinanti, penuh kelembutan dan bimbingan, sering digunakan untuk nasihat orang tua kepada anak; Asmarandana, menggambarkan cinta, kasih, dan ketulusan hati; dan Dangdanggula, melukiskan kebahagiaan dan keseimbangan hidup.
Melalui tembang-tembang ini, anak-anak diajak belajar berbudi, berbahasa indah, dan berperilaku santun. Sayangnya, seni luhur ini kian terpinggirkan. Sekolah jarang mengajarkannya, guru seni karawitan makin langka, dan ruang tampil nyaris tak ada. Akibatnya, generasi baru kehilangan hubungan emosional dengan seni daerahnya sendiri.
Keberhasilan Raska Al Ghifari dan teman-temannya di FTBI tak lepas dari peran guru yang bekerja dengan dedikasi luar biasa. Meski tanpa anggaran dan fasilitas memadai, mereka terus menumbuhkan semangat siswa untuk mencintai budaya lokal.
Keterbatasan fasilitas dan anggaran ini, diakui H. Hari Setiono, Kadis Pendidikan Kabupaten Lebak. “Untuk kegiatan FTBI memang tidak ada anggaran, fasilitas masih minim. Namun, program tersebut harus tetap berjalan, untuk menanamkan kepada anak-anak agar cinta bahasa dan budaya daerahnya sendiri,” kata Hari Setiono, Senin (26/10/2025).
Selain keterbatadan anggaran dan fasilitas, tantangan lain di Lebak, adalah: belum memadainya tenaga guru bahasa sunda dan karawitan yang khusus mengajar bahasa dan seni daerah. Anak-anak belajar secara otodidak, mengandalkan media digital.
Situasi ini kontras dengan masa 1980–1990-an, saat di sekolah di Lebak, masih ada tokoh-tokoh pengajar seni Sunda seperti Pak Odih, Bu Wawat (alm), atau Pak Sahri (alm), Ibu Siti Salamah, yang menjadi panutan dan pembimbing generasi muda di bidang seni kawih sunda.
Pendidikan budaya seharusnya tidak sekadar tambahan dalam kurikulum, tetapi menjadi jiwa dari pendidikan nasional itu sendiri. Seperti kata Ki Hajar Dewantara: “Pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.”
Peran Pemerintah Daerah: Dari Wacana ke Kebijakan Nyata
Jika FTBI ingin terus tumbuh, maka Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lebak perlu menjadikannya bagian dari kebijakan strategis kebudayaan daerah. Dukungan bukan hanya berupa seremoni atau plakat penghargaan, melainkan alokasi anggaran dan program berkelanjutan.
Beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain: Pelatihan guru seni dan bahasa daerah, agar pengajaran lebih menarik dan berkualitas. Kemudian, Penyediaan fasilitas kesenian di sekolah-sekolah, seperti alat musik tradisional dan studio seni mini.
Selain itu, Festival budaya tahunan di tiap kecamatan, yang memberi ruang ekspresi lebih luas bagi pelajar, serta Kerja sama dengan komunitas budaya lokal untuk pembinaan berjenjang.
Pelestarian budaya tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Ia membutuhkan dukungan politik dan kebijakan publik yang berpihak pada kebudayaan. Bahasa ibu adalah akar eksistensi bangsa. Ia mengajarkan bagaimana manusia berkomunikasi dengan sesamanya, lingkungannya, dan Tuhan. Ketika bahasa ibu mati, yang lenyap bukan sekadar kosakata—tetapi cara pandang, filosofi, dan jati diri bangsa. –(***)